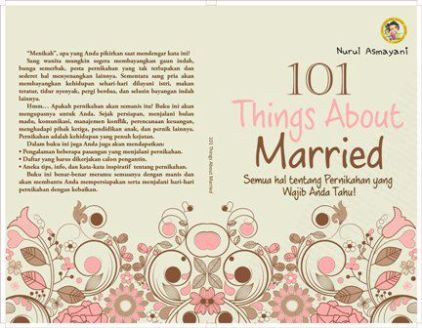Lagi, pedih itu mencabik hati bagai sayatan luka yang dipercikkan air garam. Tak berbilang sudah berapa kali aku menangis sendiri seperti ini. Luruh menjadi-jadi, pilu bertubi-tubi. Ya, aku tahu, sejak awal, upaya ini memang tidak mudah, tapi tak pernah sangka sakitnya begini. Tergugu, meski hari masih pagi.
“Jangan pegang..!. Biar Doni sendiri. Biar saja begini!. ”
“Don, jangan seperti itu. Bunda cuman mau merapikan bajumu.”
Ku lepas tanganku dari kerah baju Doni, menatap menyerah. Lalu berdiri, menciumi tangan suamiku yang baru saja menegur Doni. Doni juga langsung melengos ke arah mobil, menunggu sebelum akhirnya diantar ke sekolah. Pagi ini seperti biasa, satu ke tempat kerja, satu-nya lagi ke sekolah. Pedih yang sama, hanya saja untuk rasa ini aku belum juga mampu terbiasa, meski masa luka ini hampir menggenapi angka 4 tahun.
Doni dan Ayahnya. Dua lelaki penting dalam hidupku. Aku, wanita penting dalam hidup Ayah Doni. Tapi tak demikian bagi Doni, karena aku hanya-lah sebatas istri Ayahnya. Bahkan mengakuiku sebagai Bunda Tiri-nya saja Doni sama sekali tak sudi. Ibu kandung-nya meninggal di usia 5 tahun, selang setahun kemudian aku hadir di rumahnya mengenalkan diri sebagai Bunda. Di hari pertama juga, sayatan luka itu hadir pertama kali. Diabaikan. Di tiap kesehariannya Doni lebih mengandalkan asisten rumah tangga untuk mengurusi dirinya. Jangankan menciumnya, memeluknya, menyentuhnya saja bak kotoran hinggap di kulitnya. 4 tahun, sepanjang itu aku merindui kasihnya sebagai anak, yang takkan pernah hadir dalam rahimku. Tumor menggerogoti rahimku, meluluhlantakkan harapanku setelah setahun menantikan adik Doni hadir di tengah kami.
Dan hari-hariku pun kulalui dengan upaya meraih kasih sayang Doni, anak semata wayang kami. Salah satu lelaki penting dalam hidupku.
Panjang juga menanjak. Duri perjalanan meraih kasih ini terhempas depan aral pandangku. Kabut putus asa mulai singgah. Luka-luka yang setiap pagi kuncupnya memekar, kini merekah hingga perihnya ke ulu jiwa. Aku termangu menatapi gambar kedua lelaki-ku. Katakanlah aku gagal menjadi istri, menjadi Ibu juga tak termasuk dalam takdirku, apalagi menjadi perempuan tulen..aku pun bukan satu di antaranya.
Ku sentuh raut wajah lelaki tinggi berkacamata di figura poto, tak sadar air mata yang sedari tadi menggantung akhirnya jatuh. Satu-satunya lelaki penting inilah yang senantiasa menguatkanku. Segala pengabdianku kurasa tak kan pernah cukup mengganti cinta-cintanya. Tidak akan pernah.
“Aku menyerah Ayah, aku menyerah..”
Segera kuletak figura poto itu. Melangkah keluar, menenteng tas pakaianku, hendak sembuhkan semua luka-luka menganga ini.
**Flash Fiction ini diikut sertakan dalam kuis kamis 4-11 april 2013 bersama IIDN.